Pengarang Buku : Tulus Tambunan
Sejak krisis utang luar negri (ULN) dunia pada awal 1980-an, masalah ULN yang dialami oleh banyak negara sedang berkembang (NSB) tidak semakin baik. Banyak NSB semakin tejerumus ke dalam krisi ULN smapai negara-negara pengutang besar terpaksa melakukan program-program pemyesuaian struktural terhadap ekonomi mereka atas desakan dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), sebagai syarat utama untuk mendapatkan pinjaman baru atau pengurangan terhadap pinjaman lama.
Tingginya ULN dari banyak NSB disebabkan terutama oleh tiga jenis defisit : defisit transaksi berjalan (TB) atau di dalam literatur umum disebut trade gap, yakni ekspor (X) lebih sedikit daripada impor (M). Dari faktor-faktor tersebut, defisit TB sering disebut di dalam literatur sebagai penyebab utama membengkaknya ULN dari banyak NSB. Besarnya defisit TB melebihi surplus neraca modal (CA) (kalau saldonya memang positif) mengakibatkan defisit neraca pembayaran tahun negatif, maka CD dengan sendirinya kana habis jika tidak ada sumber-sumber lain (misalnya modal asing dari luar negri), seperti yang dialami oleh negara-negara miskin dibenua Afrika. Padahal devisa sangat dibutuhkan terutama untuk membiayai impor barang-barang modal dan pembantu untuk kebutuhan kegiatan produksi di dalam negri.
Sejak pemerintahan orde baru hingga saat ini tingkat ketergantungan Indonesia pada ULN tidak pernah menyurut, bahkan mengalami suatu akselerasi yang pesat sejak krisis ekonomi 1997/98, karena pada periode tersebut pemerintah Indonesia terpaksa membuat utang baru dalam jumlah yang besar dari IMF untuk membiayai pemulihan ekonomi. Arus modal asing terdiri atas arus PLN atau ULN dan investasi. Arus ULN terdiri atas utang jangka panjang, ULN-LR ( lebih dari 1 tahun), dan utang jangka pendek, ULN-SR (kurang dari atau hingga satu tahun). Arus investasi dari luar negeri bisa dalam bentuk PMA (disebut investasi langsung jangka atau jangka panjang) dan investasi portofolio (disebut investasi tidak langsung atau jangka pendek).
Selain itu, perkembangan ULN dapat dianalis melalui pedekatan permintaan dan penawaran utang. Kenaikan pendapatan dan selanjutnya belanja masyarakat cenderung menaikan impor, baik barang konsumsi maupun barang modal dan penolong serta bahan baku untuk keperluan industri dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya di dalam negeri.
Idealnya jika sebuah negara telah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu atau pada tahap akhir dari proses pembangunan, ketergantungan negara tersebut terhadap PLN akan lebih rendah dibandingkan pada saat negara itu baru mulai membangun.
2. PERKEMBANGAN ULN INDONESIA
Besarnya akumulasi ULN, terutama sangat terasa setelah krisis ekonomi 1997/98, memaksa pemerintah Indonesia mengatur secara khusus atau mengubah paradigma soal penanganan PLN di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 khususnya untuk ULN pemerintah. Sebagai alternatif pembayarannya, pemerintah berusaha agar deifisit APBN didanai lewat penerbitan obligasi atau SUN.
Ketergantungan pemerintah terhadap ULN untuk membiayai defisit APBN-nya memang sangat berbahaya, ketergantungan terhadap ULN akan memperbesar defisit APBN, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap idak berubah, yang selanjutnya menambah ketergantungan pada ULN.
Mengurangi secara bertahap pembiayaan pembangunan dengan memakai ULN, yang merupakan selisih antara pencairan pinjaman baru dan pembayaran pokok utang. Membenahi mekanisme dan prosedur pelaksanaan PLN, termasuk perencanaan, proses seleksi, pemanfaatan, dan pengawasannya. ULN pemerintah harus dikelola secara transparan dan selalu dikonsultasikan dengan DPR dan diatur dengan undang-undang.
Memanfaatkan pinjaman secara optimal sesuai dengan prioritas pembangunan dan dilaksanakan secara transparan, efektif, dan efisien. Mengkaji secara menyeluruh kemampuan setiap proyek dan mempertajam prioritas pengeluaran anggaran dengan memperkuat pengawasan yang sistematik, utamanya bagi proyek-proyek yang dibiayai dari ULN. Meningkatkan kemampuan diplomasi dan negoisasi PLN untuk memperoleh jangka waktu dan pola persyaratan yang memudahkan proses pencairan dan mempeingan beban pembayaran. Melakukan restrukturasi ULN, termausk permohonan pemotongan utang dan penjadwalan kembali ULN dengan para donor secara transparan dan dikonsultasikan dengan DPR.
Di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003 tentang pengendalian jumlah kumulatif defiisit APBN dan APBD (anggran pendapatan dan belanja daerah) serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga diatur bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dari PDB dan pinjaman (jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dibatasi paling besar 60% dari PDB.
Sejak pemerintahan orde baru hingga saat ini tingkat ketergantungan Indonesia pada ULN tidak pernah menyurut, bahkan mengalami suatu akselerasi yang pesat sejak krisis ekonomi 1997/98, karena pada periode tersebut pemerintah Indonesia terpaksa membuat utang baru dalam jumlah yang besar dari IMF untuk membiayai pemulihan ekonomi. Arus modal asing terdiri atas arus PLN atau ULN dan investasi. Arus ULN terdiri atas utang jangka panjang, ULN-LR ( lebih dari 1 tahun), dan utang jangka pendek, ULN-SR (kurang dari atau hingga satu tahun). Arus investasi dari luar negeri bisa dalam bentuk PMA (disebut investasi langsung jangka atau jangka panjang) dan investasi portofolio (disebut investasi tidak langsung atau jangka pendek).
Selain itu, perkembangan ULN dapat dianalis melalui pedekatan permintaan dan penawaran utang. Kenaikan pendapatan dan selanjutnya belanja masyarakat cenderung menaikan impor, baik barang konsumsi maupun barang modal dan penolong serta bahan baku untuk keperluan industri dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya di dalam negeri.
Idealnya jika sebuah negara telah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu atau pada tahap akhir dari proses pembangunan, ketergantungan negara tersebut terhadap PLN akan lebih rendah dibandingkan pada saat negara itu baru mulai membangun.
2. PERKEMBANGAN ULN INDONESIA
Besarnya akumulasi ULN, terutama sangat terasa setelah krisis ekonomi 1997/98, memaksa pemerintah Indonesia mengatur secara khusus atau mengubah paradigma soal penanganan PLN di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 khususnya untuk ULN pemerintah. Sebagai alternatif pembayarannya, pemerintah berusaha agar deifisit APBN didanai lewat penerbitan obligasi atau SUN.
Ketergantungan pemerintah terhadap ULN untuk membiayai defisit APBN-nya memang sangat berbahaya, ketergantungan terhadap ULN akan memperbesar defisit APBN, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap idak berubah, yang selanjutnya menambah ketergantungan pada ULN.
Mengurangi secara bertahap pembiayaan pembangunan dengan memakai ULN, yang merupakan selisih antara pencairan pinjaman baru dan pembayaran pokok utang. Membenahi mekanisme dan prosedur pelaksanaan PLN, termasuk perencanaan, proses seleksi, pemanfaatan, dan pengawasannya. ULN pemerintah harus dikelola secara transparan dan selalu dikonsultasikan dengan DPR dan diatur dengan undang-undang.
Memanfaatkan pinjaman secara optimal sesuai dengan prioritas pembangunan dan dilaksanakan secara transparan, efektif, dan efisien. Mengkaji secara menyeluruh kemampuan setiap proyek dan mempertajam prioritas pengeluaran anggaran dengan memperkuat pengawasan yang sistematik, utamanya bagi proyek-proyek yang dibiayai dari ULN. Meningkatkan kemampuan diplomasi dan negoisasi PLN untuk memperoleh jangka waktu dan pola persyaratan yang memudahkan proses pencairan dan mempeingan beban pembayaran. Melakukan restrukturasi ULN, termausk permohonan pemotongan utang dan penjadwalan kembali ULN dengan para donor secara transparan dan dikonsultasikan dengan DPR.
Di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003 tentang pengendalian jumlah kumulatif defiisit APBN dan APBD (anggran pendapatan dan belanja daerah) serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga diatur bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dari PDB dan pinjaman (jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dibatasi paling besar 60% dari PDB.


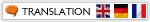


0 comments:
Post a Comment